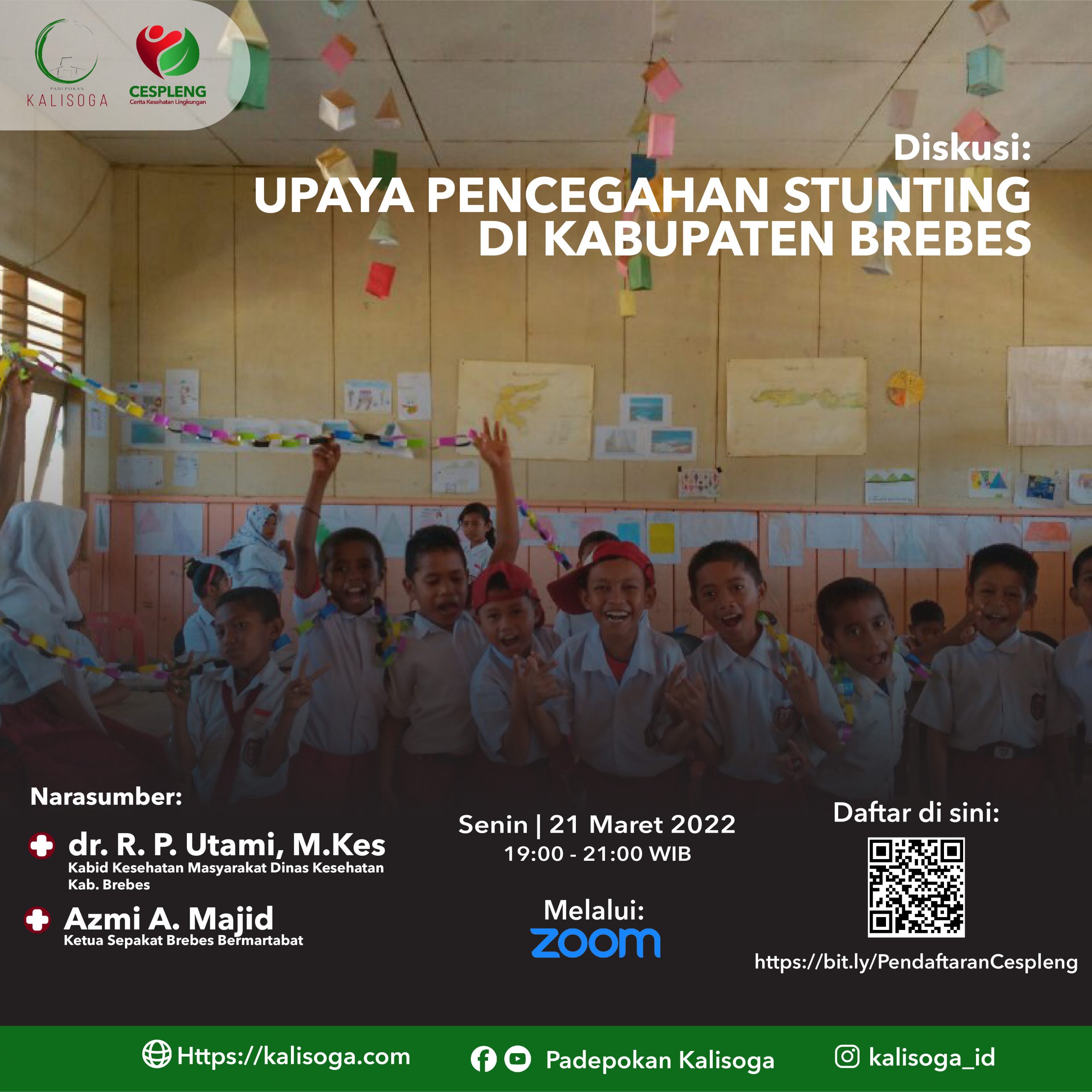Post Power Syndrome (PPS) dan Demokrasi Kita

Foto : Sudirman Said[/caption]
Jakarta – Post Power Syndrome (PPS) sering diterjemahkan secara bebas sebagai “sindroma pasca kekuasaan”. Suatu gejala (negatif) yang dialami atau ditampilkan oleh orang-orang yang tidak lagi memegang kekuasaan, jabatan, atau pengaruh tertentu dalam hidupnya.
Perasaan tidak sekuat di masa lalu, tidak lagi dianggap penting, merasa tidak dihormati, hingga hilangnya previlese sering menjadi pemicu dari gejala PPS itu.
Para ahli kesehatan jiwa mengidentifikasi sejumlah gejala yang dialami oleh penderita PPS, antara lain: kurang bergairah, mudah tersinggung, menarik diri dari pergaulan, sikap yang tidak mau kalah, sulit mendengar pandangan pihak lain, dan secara repetitive suka membicarakan kebesaran diri dan kekuasaan di masa lalu.
Suatu tindak-tanduk yang menggangu bukan?. Karena itu, bagi kebanyakan orang, kehilangan kekuasaan dan berhenti dari suatu jabatan, boleh jadi merupakan hal yang amat ditakuti.
Bangsa dan Negara Indonesia kita, sudah memilih jalan demokrasi sebagai cara bernegara. Demokrasi mensyaratkan sirkulasi kepemimpinan publik. Secara berkala pemimpin dipilih dan diangkat, lantas suatu saat harus berhenti karena dibatasi konstitusi dan regulasi. Mereka berhenti karena berbagai sebab: diberhentikan, tidak terpilih lagi, atau sesederhana memang sudah habis masa tugasnya. Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota, Bupati dan wakilnya akan berganti,
Para pejabat yang membantu para pemimpin politik seperti Menteri, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direksi dan Komisaris BUMN/D juga akan mengalami rotasi, mutasi, atau berhenti bila waktunya tiba. Pun demikian para anggota dan Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota semuanya akan mengalami pergantian pada waktunya. Inilah indahnya demokrasi. Hadirnya pemimpin baru diharapkan membawa kebaruan dan, tentu saja, perbaikan dalam menjalankan amanat kepemimpinannya.
Keadaan ini seharusnya disadari oleh setiap pemangku jabatan publik, dan karenanya setiap pejabat publik harus bersiap untuk kehilangan posisinya. Hanya soal waktu setiap pejabat public akan berhenti, dan dengan demikian akan kehilangan previlese, kekuasan, dan pengaruhnya. Ini berarti, pada setiap siklus politik, sejumlah orang berpotensi mengalami PPS.

Pertanyaanya: bagaimana menghindari post power syndrome?. Mudah saja. Berikut ini beberapa tips untuk menghindari PPS.
Pertama, harus selalu diingat bahwa jabatan itu milik publik; otoritas dan kekuasaan adalah pinjaman dari publik yang suatu saat harus dikembalikan pada pemiliknya. Karenanya, tidak ada alasan untuk memegangnya terus menerus.
Kedua, ketika duduk dalam kekuasan, jangan terlalu menikmati berbagai previlese atau fasilitas yang disediakan. Gunakan fasilitas dan keleluasaan (diskresi) sewajarnya saja untuk keperluan pelaksanaan tugas publik; sehingga ketika previlese dan diskresi itu hilang, tidak merasakan kehilangan yang berlebihan. Ketiga, topanglah kekuasaan dengan kekuatan personal berupa pengetahuan, wawasan, kapasitas, dan kompetensi kepemimpinan sejati. Otoritas formal yang tidak dibarengi dengan kompetensi tidak akan memberikan manfaat maksimal, sebaliknya dapat menimbulkan banyak kemudharatan. Keempat, harus disadari bahwa disamping memberikan keleluasan, kebesaran dan keistimewaan, kekuasaan juga bermakna tanggung jawab, pelayanan, dedikasi, dan pengorbanan.
Bila kekuasaan dipandang secara utuh dari banyak sisi, maka tak ada alasan bagi siapapun untuk “nggendoli” jabatan dan kekuasaan secara membabi buta. Akhirnya, jangan berkhianat, jangan korupsi, dan jangan bertindak melampaui batas. Bagi penguasa yang lalim, berakhirnya masa jabatan adalah mimpi buruk; sebaliknya bagi pemimpin yang adil selesainya tugas akan disongsong dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Demokrasi kita harus dibersihkan dari para pengidap PPS.
Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri.
Sudah dipublikasikan melalui detik.com | Post Power Syndrome (PPS) dan Demokrasi Kita (detik.com)