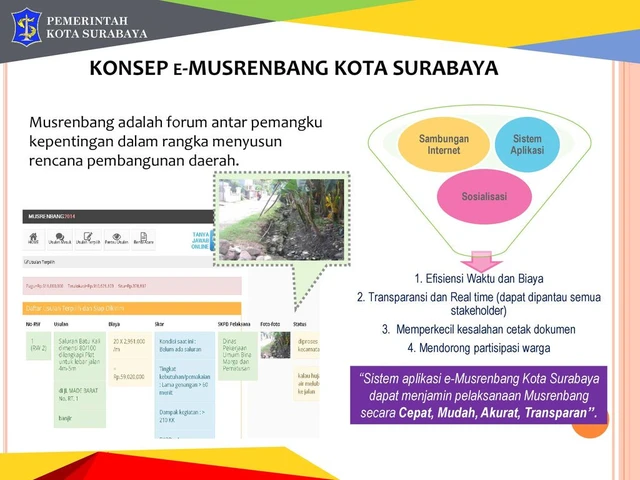Assalamualaikum wr. wb.
Pertama-tama, izinkan saya menyebut Saudara-saudara bukan dengan panggilan “anak-anakku”, bukan “adik-adikku”. Bukan “mahasiswa-mahasiswiku”. Tetapi, Sengaja saya pilihkan panggilan yang kuat aroma kesetaraan dan kebangsaannya, yaitu: “Jong Indonesia”!
Jong itu Bahasa Belanda, artinya: orang muda. Bacanya: “Yong”. Nama Jong Indonesia seperti merekam elan kebangsaan. Juga kebanggaan, kejuangan, dan harapan-harapan baik orang muda.
Jong Indonesia pernah menjadi nama perkumpulan pemuda sejak Februari 1927. Ia cikal-bakal utama dari Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.
Dari kongres itu, disepakati “Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia”. yang pada 30 tahun kemudian namanya diubah menjadi “Sumpah Pemuda”, oleh Bung Karno.
Jadi, kata “Sumpah Pemuda” itu munculnya bukan langsung pada 1928, tapi pada 1958.
Setahun sebelum Sumpah Pemuda, Pada Desember 1927, nama Jong Indonesia diganti menjadi “Pemuda Indonesia.” Jadi, nama Jong Indonesia eksisnya hanya 10 bulan. Magis Jong Indonesia seperti ditidurkan cukup lama. Maka, tak ada salahnya jika kita ambil kembali. Kita bangunkan. Kita hidupkan. Kita nyalakan apinya.
Apakah api Jong Indonesia? Jong Indonesia adalah api yang hidup di antara pemuda perumus dan peletak fondasi kebangsaan, dengan semangat “harkat ber-Indonesia”.
Dengan demikian ada dua kata kunci di sini: (1) muda, (2) berharkat. Dan, bagi kita, di Universitas Harkat Negeri, muda itu bukan soal usia. Tapi soal semangat dan daya juang. Sepakat, ya?
Jadi, kalau saya sapa Saudara-saudara dengan “Jong Indonesia!”, balas dengan teriakan: “Kami Muda, Kami Berharkat”. Jangan lupa, kepalkan tangan kanan. Setinggi-tingginya.
Mari, kita coba...
“Jong Indonesiaaaa...!”... (3 kali)
“Kami Muda, Kami Berharkat!”
Perayaan vs Peringatan
Saudara-Saudara, hari ini kita menyelenggarakan perayaan, mengingat kembali hari Sumpah Pemuda, yang terjadi 97 tahun lalu.
Kalau kita ingat-ingat, betapa sibuknya kita pada segala perayaan ini dan itu. Apalagi dengan pasang baliho besar-besar, didominasi wajah-wajah pejabat, bagaikan kandidat Pilkada.
Saya mau tanya sekarang. Dari waktu ke waktu, adakah perayaan-perayaan semacam itu menorehkan kesan di hati? Atau mendesakkan kuat-kuat spirit kejuangan di level aksi?
Rasa-rasanya kok tidak. Atau belum. Karena, perayaan macam itu tidak lebih dari sekadar suatu rutinitas yang monoton. Tidak menyisakan apa-apa kecuali letih, lelah, dan sisa-sisa pesta. Slogan-slogannya klise.
Betapa seringnya kita terjebak... hanya bicara-bicara, tanpa makna.
Kita sering bersemangat menata bungkus, tapi lalai menyiapkann isinya.
Heboh di seremoni, tapi tak peduli substansi
Gagah perkasa dalam slogan, tapi lemah dalam aksi.
Tidak ada yang salah dengan perayaan. Yang salah adalah karena itu kita jadikan sekadar check list pemenuhan kewajiban saja. Bukan berdasar kesadaran tentang apa maknanya.
Di kampus ini, Universitas Harkat Negeri, kita harus dobrak tradisi perayaan tanpa makna. Yang kita maui adalah memaknai “peringatan” dengan sungguh-sungguh. Menjadi refleksi. Menjadi kesempatan tadabbur. Refleksi untuk apa? Refleksi untuk mewarisi apinya sejarah kejuangan. Bukan abunya!. Mengapa? Karena ..
Dalam peringatan, kebersihan niat dan akal-budi dikedepankan.
Dalam peringatan, ketajaman kritik dan koreksi didorongkan.
Dalam peringatan, kesegaran tafsir dan diksi dihadirkan.
Karena itu, sepulang dari sini, lelah dan letih Anda harus terbayar. Energi semangat harus terisi penuh kembali. Jiwa saudara-saudara harus disuburkan. Tekad bulat menata masa depan kalian, harus dipancangkan. Apalagi, hari ini adalah Hari Pengingatan Sumpah Pemuda! Harinya orang-orang muda seusia Saudara-Saudara.
Wahai Jong Indonesia, tangkaplah api Sumpah Pemuda. Bangunkan energi kejuanganmu dengannya. Kembalikan elan juang. Kembalikan jiwa pergerakanmu, sebagaimana jiwa-jiwa para pelaku Sumpah Pemuda 1928. Bersiaplah menjawab pertanyaan mendasar yang semakin merisaukan: “Hari-hari ini, akan dibawa ke mana Indonesia kita?”
Kalian, Jong Indonesia wajib menjawab pertanyaan ini, sebab kalian lah pemilik masa depan yang sesungguhnya...
Pelajaran Ber-Indonesia
Saudara-Saudara sebangsa dan se-Tanah Air...
Seperti halnya kalian para mahasiswa, saya pun pernah muda. Kita semua pernah muda. Pernah merasakan bunga-bunga gelora muda, dan gelegak masa muda.
Setiap orang-muda, punya masanya. Setiap masa, punya orang-mudanya. Mari kita tengok dinamika orang-orang muda pada masa itu.
Sumpah Pemuda 1928 tidak sekonyong-konyong lahir. Ada konteks dan pemicunya. Pemicu utamanya adalah, dijalankannya Politik Etis oleh Pemerintah Kolonial Belanda sejak 17 September 1901. Suatu politik balas budi dari “bangsa pemerintah” kepada “bangsa terperintah”; dari bangsa kolonial yang penjajah, kepada bangsa koloni yang terjajah.
Wujud programnya ada tiga, yaitu: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Sebenarnya tiga alat itu, diberikan bukan semata didasari maksud baik pemerintah kolonial. Tetapi terselip pula agenda kebutuhan praktis dan pragmatis.
Program edukasi, misalnya, itu untuk mencetak tenaga-tenaga kerja siap-pakai buat kepentingan kolonial juga. Program irigasi dijalankan untuk memperbaiki pengairan bagi kebun-kebun yang hasilnya akan diambil oleh pemerintah kolonial. Pun program emigrasi adalah usaha memindahkan tenaga kerja untuk mendukung penyelenggaraan masif ekonomi mereka.
Tetapi, alam semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa, bekerja dengan caranya. Ternyata, berkat program edukasi, tak dinyana, malah tumbuh tunas-tunas kesadaran berbangsa. Program edukasinya Politik Etis justru melahirkan agen-agen muda cerdas-tercerahkan. Para pejuang. Para perintis kemerdekaan. Sesuatu yang sudah pasti tidak diinginkan Belanda.
Mereka berjamaah di Jong ini, Jong itu. Juga di berbagai daerah dan komunitas. Gaya mereka berbeda dengan pendahulunya. Kalau pendahulunya lebih menekankan kerja otot, mereka kerja otak. Kerja intelektual. Medan laga mereka bernama pers, organisasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dll. Dari banyak daerah dan etnis, lalu berhimpunlah mereka di Kongres Pemuda.
Semula, orbit perjuangan mereka lebih berkutat pada wilayah kesenasiban masing-masing. Masih primordial. Jong Java, misalnya, dibentuk hanya di dan untuk selingkup orang Jawa. Sekar Rukun, ya hanya untuk orang Sunda. Begitu pula Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, dll.
Pertanyaannya, apa yang mendorong mereka harus bersatu dan ber-Indonesia? Jawabnya satu, yakni: karena sama-sama punya perasaan senasib sebagai bangsa terperintah. Bangsa terjajah. Karena adanya keinginan kuat mereka untuk menjadi bangsa yang lepas dari penindasasan, dari ketidakadilan, dan dari kesewenangan. Mereka bersatu karena semangat yang berkobar-kobar untuk menjadi bangsa merdeka... dalam arti yang seluas-luasnya.
Begitulah kurang-lebih asal-usul “ber-Indonesia” dalam konteks orang-orang muda kala itu. Sejarah pun mencatat, para Jong itu bukan saja penanda zaman, tapi bahkan lokomotif perubahan. Visi yang mereka pancangkan melalui kerja-kerja cerdas, inklusif, berdikari, dan sikap setara, senasib sepenanggungan pun bunyinya masih relevan sampai sekarang.
Tak butuh waktu lama, katalis Politik Etis membuat mereka lekas menyadari dua hal, yakni:
- Kesadaran bahwa perjuangan itu harus ditempuh dengan cara menghimpun diri sebagai bangsa “yang satu”. Mengapa? Agar jelas betul “jenis kelaminnya”: mana bangsa terperintah (kawan) dan mana bangsa pemerintah (lawan). Nah, nama yang mereka angkat dan sepakati untuk menyebut “yang satu” itu, adalah “Indonesia”.
- Ternyata, “campur tangan” Tuhan untuk memerdekakan Indonesia itu ditaruh-Nya pada “buah tak terduga” dari program edukasi atau pendidikan-nya Politik Etis. Gerakan mereka bukan tak berelasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tonggak pertama, berdirinya Budi Utomo pada tujuh tahun setelah Politik Etis dirilis, itu adalah “buah tak terduga” dari pohon pendidikan. Tonggak kedua, yakni Sumpah Pemuda 1928, itu “buah tak terduga” juga dari pohon pendidikan. Bahkan, kemerdekaan 1945 pun demikian: golongan muda bertarung ide dengan golongan tua.
Oleh karena itu, kita, sivitas akademika Universitas Harkat Negeri, harus sadar. Kita ini sejatinya adalah anak kandung dan penerus dari spirit luhur itu. Oleh sebab itu, tugas kita di sini, kewajiban kita disini, adalah:
- membuahkan sebanyak-banyaknya anak muda terdidik-tercerahkan,
- dari pohon pendidikan dengan segala manifestasinya,
- demi seluas-seluas kebermanfaatan bagi orang banyak,
- bagi rakyat, bagi bangsa, bagi kemanusiaan seluruhnya.
Muda, Berharkat
Mari kita kenali lebih dekat beberapa tokoh di Jong Indonesia 1927, generasi pencetus Sumpah Pemuda 1928. Tersebutlah nama Sugondo Joyopuspito. Ia mahasiswa RHS (Recht Hoge School, Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia, ketua panitia Kongres Pemuda II.
Saat kuliah, Sugondo aktivis pergerakan. Progresif. Padahal, sebagian besar pribumi pegawai-pegawai kolonial alergi dengan label “pergerakan”. “Bikin susah hidup,” katanya.
Sistem kepegawaian kala itu bisa memaksa para orang tuanya tutup-kuping tutup-mulut, atau berbohong, atau ABS (Asal Bapak Senang) saja terhadap perilaku buruk pemerintah kolonial. Tetapi, kondisi itu justru memicu kesadaran anak-anak mereka agar praktik-praktik semacam itu dihentikan.
Tak jarang dunia pergerakan di lingkungan kampus menjadi penyebab gagalnya kuliah parah aktivis pergerakan sebagaimana nasib Sugondo. Oleh karena waktu Sugondo banyak tersedot untuk menentang penjajah melalui dunia pergerakan, setahun setelah Sumpah Pemuda, dia di-drop out oleh kampusnya.
Ada satu lagi. Arnol Mononutu, namanya. Ia teman satu indekos Sugondo. Aktivis Jong Celebes ini juga pernah gagal kuliah karena alasan serupa. Ketika kuliah di Belanda, biaya hidup Arnold distop. Penyebabnya adalah, Pemerintah Hindia Belanda mengintimidasi orang tuanya yang pegawai pemerintah itu.
Ini catatan kaki saya. Saya tentu tidak bermaksud membela para mahasiswa yang keteteran kuliah, malas kuliah, atau IP jelek. Bukan. Bukan sama sekali. Dalam kondisi apa pun, studi tetap harus menjadi prioritas.
Hanya saja, imbangi studi itu dengan atensi kalian pada kondisi bangsa. Salah satunya melalui jalan “pergerakan”. Aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, ikut-serta dalam forum-forum diskusi. Di sanalah pikiran kalian akan diasah, semangat juang akan ditempa, dan jiwa merdeka Saudara-saudara akan terus diperkuat.
Apa yang bisa dipetik dari cerita Sugondo dan Arnold tadi? Betapa dalam usia yang masih bau kencur, awal 20-an tahun, mereka yakin betul pada pilihan luhur. Pilihan itu adalah: “hidup berharkat dalam kemerdekaan, bukan hidup nikmat dalam rezim dan tabiat penjajah”. Ketika Kemerdekaan yang mereka perjuangkan belum terjadi, maka jalan pergerakan adalah pilihan mereka!
Saudara-saudara sekalian.....
Muhamad Tabrani, pada pidato sambutannya sebagai Ketua Panitia Kongres Pemuda I, 26 April 1926, menegaskan:
“... Kita semua—orang-orang Jawa, Sumatera, Minahasa, Ambon, dll.—oleh sejarah dijadikan makhluk yang harus saling mengulur tangan dalam kita mencapai apa yang menjadi cita-cita kita semua; yaitu kemerdekaan Indonesia, Tanah Air yang kita cintai.”
Penyelenggaraan Ilahi
Saudara-saudara.... buah dari tindakan Jong Indonesia itu luar biasa dampaknya. Kala itu, semua elemen orang muda seperti tengah berlomba untuk men-stempel dirinya sebagai “Indonesia”. Bahkan, menjadi sejenis demam “akulah yang paling Indonesia!”
Tiba-tiba saja “Indonesia” diterima sebagai identitas nasional. Wilayahnya, Indonesia. Bangsanya, Indonesia. Bahkan bahasanya pun, Indonesia. Padahal, negara dan pemerintahnya, belum lahir. Patih Gajah Mada saja, dengan “Sumpah Palapa"-nya itu, toh tak pernah bisa mempersatukan Nusantara. Sumpah Palapa itu sekadar testamen politik.
Artinya, belum pernah ada satu penguasa pun yang berhasil mempersatukan Indonesia kecuali kaum tahun 1928 itu. Jong-jong itu. Sumpah Pemuda menciptakan persatuan Indonesia sebelum pemerintah Indonesia mengusahakan persatuan.
Itu semua dari dan oleh rakyat. Yang pelakunya didominasi oleh orang muda. Itulah kenyataan sejarah.
Tentang “kenyataan sejarah” tersebut, penyair WS Rendra pernah berujar:
“Tidak ada satu penguasa pun yang bisa mempersatukan. Sultan Agung yang namanya Agung itu, mempersatukan Jawa saja tidak bisa. Masuk Betawi saja tidak bisa, hanya sampai Matraman, Batavia. Sampai Belanda masuk pun, tidak satu penguasa pun yang bisa mempersatukan 'Indonesia'. Belanda pun tidak bisa... Tetapi, (ternyata) bangsa Indonesia sendiri, bahkan yang anonimus itu, bisa mengatakan ‘(kami) satu bangsa, satu Tanah Air, satu bahasa’… Tidak semua bangsa bisa mendapat rahmat seperti kita!”
Coba cermati kalimat terakhir WS Rendra itu: “Tidak semua bangsa bisa mendapat rahmat seperti kita.” Ada suatu kesadaran yang subtil di situ. Yakni: ini semua mustahil terjadi tanpa adanya campur-tangan Tuhan. Suatu providentia Dei. Penyelenggaraan ilahiah.
Tujuan perjuangan proyek persatuan dari angkatan muda 1928 itu bukan demi persatuan itu sendiri, melainkan demi sesuatu yang lebih besar: kemerdekaan.
Saudara-saudara sekalian...
Hari-hari ini, kita sudah mencapai kemerdekaan. Membentuk suatu negara. Sejak 1945. Jadi, sudah 80 tahun lamanya.
Namun, kemerdekaan sebagai bangsa, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Semua ide tentang persatuan akan lekas jadi mitos belaka manakala cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa tidak sungguh-sungguh dihadirkan, apalagi sampai dinistakan.
Cita-cita merdeka itu adalah: terlindunginya segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa, serta terlibatnya kita dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Lantas, apa pentingnya Sumpah Pemuda buat orang muda sekarang? Rasa-rasanya, orang muda, para mahasiswa, saudara-saudara sekalian, memerlukan role model, sosok rujukan, figur teladan, yang bisa menemani Saudara-saudara menjawab tantangan dan problem kekinian.
Jangan ragu, jangan bimbang. Ambil saja mereka para kaum muda 1928 yang menorehkan catatan gemilang dalam perjuangan kemerdekaan kita, sebagai role model, sebagai teladan, sebagai sumber inspirasi kalian.
Teladani mereka. Bukan saja pribadinya, tapi juga nilai-nilai luhur dan elan kejuangannya. Nilai-nilai luhur dan semangat juang mereka dapat menjadi referensi dan inspirasi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan. Kewajiban kita adalah terus menjaga relevansi. Mengkinikan yang lampau, untuk kebutuhan bikin-betul dan bikin-baik bangsa ini ke depan!
Saudara-saudara, Anda sekarang sedang berada di usia-usia muda. Usia produktif. Usia yang harus melawan dekomposisi atau pembusukan. Baru-baru ini, sebuah lembaga merilis hasil surveinya. Hasilnya cukup menggembirakan saya.
Menurut survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas, pada Semester I 2025, sebagian besar (40%) orang muda Indonesia punya pandangan politik yang sudah cukup progresif. Adapun yang tergolong (sangat) progresif, konsisten di angka 49%. Artinya, orang muda Indonesia secara konsisten menaruh perhatian dan kepedulian pada nilai-nilai kesetaraan serta keadilan sosial.
Survei itu mendorongkan optimisme, bahwa tanaman yang baru saja tumbuh ini semakin menolak rontok dan busuk. Jika Anda mendapati orang-orang muda yang dulu gagah betul melawan kezaliman dan otoritarian, tapi sekarang justru masuk mendukung lingkaran kezaliman otoritarian yang dulu ia lawan, jangan ditiru. Jangan dicontoh. Jauhi. Itu adalah proses pembusukan, namanya.
Di sini, di kampus ini, kita semua sedang menempa diri, menghindar dari proses pembusukan itu. Kita tidak sedang ingin membusuk, bukan?
Belajar Kepemimpinan pada Jong Indonesia 1928
Saudara-saudara sekalian, para Jong Indonesia....
Sekarang, mari kita bicara tentang kompas moral, penjaga arah suatu perjuangan...
Muda-mudi Jong Indonesia angkatan 1928 itu telah memampangkan kepada kita tentang karakter kejuangan yang sepatutnya dimiliki. Yakni: (1) tabah dalam menghadapi tekanan; (2) berjamaah dalam kejujuran dan kompetensi; (3) manunggal dengan rakyat, serta (4) menjaga integritas dengan jalan terus bangun rekam-jejak kebaikan.
Keempat syarat kejuangan itu, oleh Doris Kearns Goodwin (2015), disebut sebagai “atribut penjaga kepemimpinan moral”. Dalam hal ini, Goodwin merujukkannya pada karakter dua presiden legendaris Amerika Serikat, yakni Abraham Lincoln dan Theodore Roosevelt
Dari jong-jong angkatan 1928 itu pula kita bisa belajar, bahwa kompas pemimpin dalam bekerja itu namanya adalah moral. Pemimpin bukan dinilai dari kata-kata manis dan sopan-santunnya, karena itu semua punya sifat manipulatif.
Pemimpin itu dinilai dari aksi nyata integritas dan komitmen dalam meneguhinya. Juga dari kesanggupannya untuk membenamkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Pada gilirannya, nilai-nilai itu akan membangun dan merebut trust publik. Publik pun akan menjadikannya sebagai standar dan panduan, terutama terkait praktik-praktik berbangsa dan bernegara.
Kepemimpinan moral perlu diiringi dengan langkah-langkah nyata mereformasi praktik bernegara dari seluruh alat Pengurus Negara. Yakni: para aparat sipil, aparat militer, aparat kepolisian, dan birokrasi seluruhnya. Perlunya, agar bersih dan efisien dalam melayani publik. Tak boleh juga dilupakan reformasi praktik-praktik politik agar mengembalikan kepercayaan publik bahwa politik adalah jalan beradab manusia masa kini untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
Untuk itu, kembalilah pada moral/etika sebagai kompas berpikir dan bertindak.
“Pendeknya, kepemimpinan moral harus kita jadikan ‘jalan pulang’ bagi bangsa yang akhir-akhir ini tengah kelelahan dirudapaksa oleh korupsi, pengkhianatan konstitusi, pembajakan demokrasi, dan gelimang praktik-praktik tak punya malu.“
Kalau boleh sedikit bermain kata...., dahulu, Politik Etis-lah yang menghasilkan “buah-buah tak terduga” melalui program-programnya. Hari ini, praktik-praktik Etika Berpolitik-lah yang semoga menghasilkan “buah-buah tak terduga” untuk bikin-betul negeri.
Semua pelajaran yang kita petik dari jong-jong 1928 itu, semoga bisa me-refresh, menyegarkan kembali sumpah atau prasetya kita pada persatuan dan bangsa ini. Melalui peringatan Sumpah Pemuda ini, kita segarkan kembali semangat juang para Jong, dengan membangun semangat baru.
Tidak lain-dan tidak bukan adalah sutau semangat: “hidup berharkat dalam (mengisi) kemerdekaan, bukan hidup nikmat dalam rezim dan bertabiat kolonial. Bukan keadaan yang memperlebar jarak antara “yang memerintah” dengan “yang diperintah”. Jarak yang lebar itu adalah warisan kolonial, yang semestinya telah diberangus melalui sejarah perjuangan para jong Indonesia. Ya, perjuangan para jong untuk menegakkan harkat ber-Indonesia!
Saudara-saudara sekalian...
saya ingin menutup pidato ini dengan mengucapkan “Selamat menunaikan ibadah refleksi Sumpah Pemuda.” Sampai jumpa di refleksi tahun mendatang dengan nyala harkat ber-Indonesia yang jauh lebih membara.
Mari kita maknai perayaan ini lebih dari sekedar rutinitas. Melainkan harus menjadi suatu peringatan. Suatu refleksi. Suatu kesempatan untuk mengingat dan memaknai kembali akan banyak hal.
Karena... dalam peringatan, kebersihan niat dan akal-budi dikedepankan.
Karena... dalam peringatan, ketajaman kritik dan koreksi didorongkan.
Karena... dalam peringatan, kesegaran tafsir dan diksi dihadirkan.
Akhir kata:
“Jong Indonesiaaaa...!” “Kami Muda, Kami Berharkat!”
“Jong Indonesiaaaa...!” “Kami Muda, Kami Berharkat!”
“Jong Indonesiaaaa...!” “Kami Muda, Kami Berharkat!”
Merdeka!!
Wassalamu’alaikum wr wb.